I’ve come to talk with you again
(Sound of silence: Simon & Garfunkel)
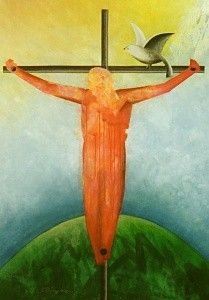
Suatu hari, dengan seorang teman kantor saya terlibat obrolan kosong. Saya tanya teman saya ini tentang minatnya ikut acara reality show televisi Fear Factor. Tumben-tumbenan, dari seorang teman cowok yang rasanya cukup punya jiwa avonturir saya mendapat jawaban, “Nggak, gw nggak mau. Gw nggak mau mati konyol. Nggak keren kalo mati konyol”. Secara spontan (tanpa “Uhuuuy” tentunya) saya merespon, “Mau mati gimana juga, judulnya mati. Lagian pas udah mati emang loe masih bisa mikirin konyol ato nggak?”.
Masih di hari yang sama, masih dengan teman yang sama, kami terlibat obrolan tentang tema yang sama; kematian. Dia bilang, “Ja, jaga-jaga gula darah kalo loe nggak mau mati gara-gara diabetes.” Banyak angota keluarganya meninggal lantaran penyakit yang satu ini. Spontan lagi (dan tanpa “Uhuuuuy” lagi), saya bilang ke dia, “Eh elo ternyata atheis yah!”. Teman saya kaget. Saya jelaskan kenapa, “Untuk orang yang ngaku berTuhan, koq bisa-bisanya elo mikir kalo orang bisa mati lantaran Diabetes?” Kelihatannya dia mengerti maksud saya, tapi dia juga hanya bisa diam dan bingung bagaimana harus merespon pertanyaan iseng saya tadi.
Bukannya mau gimana-gimana, tapi soal bagaimana atau sebab apa seseorang mati kerap mengganggu benak saya. Apa nggak aneh yah, kalo ada orang yang bilangnya beriman, rajin sembahyang punya gelar ini-itu, tapi pas ngomong tentang satu kematian, “Iya, dia meninggal karena sakit jantungnya”. Bukankah kematian merupakan satu konsekuensi hidup? Semua yang hidup secara fisik akan mati secara fisik. Saya masih membuka kemungkinan bahwa orang bisa berumur 100, 200 atau bahkan 300 tahun karena memang tidak ada hukum yang pasti bahwa orang harus mati pada umur tertentu. Tapi memang secara sosial, kalau ada orang belum mati juga di umur 300 masyarakat sekitar akan menanggapnya aneh dan si ‘oknum’ tersebut juga mungkin bakal risih diliatin orang terus. Tapi bahwa ada orang bisa hidup sekian lama, saya pernah dengar. Di India, konon orang-orang seperti itu turun gunung dari pertapaan mereka untuk hadir di sebuah festival spiritual yang diadakan 25 tahun sekali. Sayang, nama acaranya saya lupa, begitu juga dimana tempat persisnya.
Makin saya berumur hingga hari ini, makin saya mendekati usia harapan hidup orang Indonesia (berapa yah? 50 tahun something?), tentu saja topik kematian makin memikat sama memikatnya memikirkan bagaimana menikmati sisa hidup senikmat-nikmatnya. Beberapa buku dan literatur tentang kematian sempat singgah dalam benak saya. Syeh Siti Jenar yang disebut-sebut sebagai wali kesepuluh, yang oleh telaah sejarah mainstream dicap sebagai sesat, termasuk tokoh yang mensentralkan kematian dalam perenungannya. Konon baginya, hidup yang sehidup-hidupnya adalah ketika kita mengalami kematian. Memang kematian di sini bisa beragam makna, bisa fisik bisa ego. Konon, para muridnya salah mengartikan ajarannya. Mereka mencari onar di pasar supaya dipukuli massa dan akhirnya mati digebukin. Saya lebih menikmati pesan Syeh ini dalam makna kematian ego. Karena menurutnya, dalam diri kita ada RuhNya yang hanya bisa total bermanifestasi ketika diri kerdil kita mati.
Beberapa buku yang saya sempat baca juga bilang, bahwa kematian justru sebuah peristiwa yang perlu dirayakan. Saat diberitakan bahwa Paus Yohanes Paulus II telah mangkat, orang-orang Italia bertepuk tangan selama 10 menit. Konon, itu tradisi mereka untuk menghormati kematian seseorang yang sangat mereka cintai. Mungkin kematian memang perlu dirayakan, mungkin memang tak perlu harus diiringi sedu sedan, karena kematian toh sesuatu yang tak terhindarkan. Kematian adalah salah satu kepastian hukum alam. Bahkan, dalam dimensi dan wujud yang lain, sesungguhnya kematian banyak terjadi dalam hidup kita. Siang mati, hiduplah malam and vise versa. Saat kita tidur itu juga semacam kematian kecil dimana paginya kita bangun hidup kembali. Konon, kematian perlu terjadi sebagai bagian hukum kekekalan energi. Secara fisik mati, tapi energinya akan terus ada, selamanya. Seperti sepucuk daun hijau yang kemudian mati, mengering lalu terlepas dari pokoknya, jatuh ke tanah, hancur terlebur bersama tanah tapi energinya tetap ada, yang akan menjadi pupuk penyubur tanah bagi tumbuhnya biji buah yang jatuh...yang kemudian akan menjadi pohon baru...satu pokok pohon tersendiri.
Jujur saja, saya masih takut mati. Meski di sisi lain, saya mulai bisa memahami bahwa takut akan kematian adalah sebuah ketakutan yang tidak perlu. Seperti rasa takut akan datangnya senja. Tak perlu takut, senja pasti datang dengan pesonanya sendiri. Gelap malam akan menyusul. Nikmati saja, tidur saja, begitu ‘terang’ muncul kita akan bangun untuk hidup ‘berikutnya’.
Tanpa bermaksud tidak mengindahkan cara hidup sehat, saya berusaha menikmati hidup sepenuh-penuhnya. Karena rasanya, sebuah sebab kematian yang sebelumnya kerap saya pikir sebagai sebab hanyalah sebuah cara bagi berlangsungnya hukum alam, hukum semesta, hukum Tuhan. Coba saja itung-itung sendiri, berapa jumlah orang yang telah hidup sehat tanpa rokok selama hayatnya...toh mati juga oleh suatu sebab. ‘Karena’ petir, ‘karena’ kolesterol, ‘karena’ keseterum, ‘karena’ tsunami, ‘karena’ gas beracun seperti Soe Hok Gie, ‘karena’ diracun seperti Munir, ‘karena’ ketabrak seperti Lady Diana, ‘karena’ usia tua seperti Pater Drost, ‘karena’ Aids seperti Freddy Mercuri dan lain sebab. Hitung juga, berapa banyak orang yang sepanjang hidupnya tak lepas dari rokok yang bertahan sampai usia melebihi angka seratus...meski tentu saja mati juga.
Jujur saja, saya masih suka menangis ketika menghadiri sebuah perlayatan atau pemakaman. Kadang, air mata itu begitu saja jatuh. Kadang saya juga digoda suara yang bertanya; elo nangis buat diri loe sendiri atau buat orang yang baru saja mendiang? Elo menangis karena egoisme loe yang merasa ditinggalkan atau karena elo bahagia melihat temen loe telah memasuki fase lain perjalanannya? Elo menangis karena boleh berbagi kebahagian ketika hidup bersama orang yang baru saja meninggal atau karena merasa ada bahagia yang terenggut atau berkurang karena kematiannya?
Konon, buat falsafah Jawa, hidup itu seperti mampir ngombe alias numpang minum. Setelah dahaga puas kita jalan lagi. Pesan yang sama saya rasakan saat menikmati film Terminal-nya Tom Hanks. Hidup seperti sebuah persinggahan ‘sebentar’ dimana kita diberi kesempatan menjadi pribadi yang lebih baik....setelah itu kita jalan lagi. Syukur-syukur, menjadi perjalanan terakhir...sebuah perjalanan pulang.


6 comments:
Mungkin redundan, mungkin klise, tapi tetep aja pengen bilang: tulisannya keren...
takut miskin lebih bahaya dari miskin itu sendiri...
takut mati lebih menyeramkan dari mati itu sendiri...
'cos living means dying...
Hi Ferdi, thanks for the comment. Gw denger kisah seminggu loe di nf. It's not the end of the world. Sayang kita gak sempet ngobrol banyak waktu itu. Kapan2 kita ngobrol deh.
Hi Burat, makasih dah mampir and comment. Sering2 yah hehehehehe. Gimana diskusi cerpen bareng Dayat-nya? Kapan launching bukunya? Punya blog juga Rat?
hidup jaja...
mampus lu ja!
pakabar ja?
selanjutnya terserah jaja
qeqeqeqeqe
terima kasih kembali.blog punya tapi belum dibagi ke orang lain,masih malu,masih kurang lucu Pak Jaja...hehe...tapi kalo emang pengen mampir burat.blogspot.com
kalo kata bimob bilang ja: "semua org pasti mati, tinggal soal waktu".
Post a Comment